Komunikasi Pejabat Publik & Tantangannya di Zaman Digital
 Buruknya komunikasi publik, bersumber: diremehkannya logika publik oleh pemi...
Oleh Firman Kurniawan S
Buruknya komunikasi publik, bersumber: diremehkannya logika publik oleh pemi...
Oleh Firman Kurniawan S


Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi ²©²ÊÍøÕ¾Indonesia.com
Relasi baik tanpa narasi adalah sebuah kearifan. Sebaliknya, narasi bagus tanpa relasi baik hanya akan melahirkan pencitraan tanpa makna.
Dalam realita kehidupan masa kini, dua fenomena itulah yang sering ditemukan. Bagi sebagian orang kota, pilihan sikap membangun relasi baik tanpa harus mengumbar kebaikannya di ruang publik seakan menjadi sebuah kenaifan sikap. Pemahaman terhadap relasi baik di sini ditujukan pada ikhtiar menjalin hubungan melalui aktivitas, kegiatan atau kerja-kerja positif buat kemaslahatan publik.
Pada masa lampau, kearifan berbuat baik tanpa banyak berbicara, sepertinya sudah menjadi nilai budaya yang terinternalisasi di dalam masyarakat lokal negeri ini. Kearifan ini juga sejalan dengan ajaran agama yang meminta kepada setiap umatnya ketika tangan kanan berbuat baik maka tangan kiri tidak harus mengetahuinya.
Sayangnya, sikap hidup semacam itu sudah tak lagi banyak yang menghidupkannya di masa kini. Pragmatisme hidup seakan menjadi pilihan yang paling mudah untuk dijalankan bagi masyarakat yang tinggal di kota kota besar. Kita seakan tak malu lagi untuk menyuarakan "ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang". Bentuk sayang ini juga berkorelasi pada kekuasaan.
Cara-cara semacam ini umumnya semakin banyak ditemui menjelang datangnya pesta demokrasi. Setahun menjelang pilkada serentak serta Pemilu 2024, kita menjadi semakin akrab untuk menyaksikan fenomena semacam itu.
Saat ini, ruas jalan utama atau ruang publik sudah semakin banyak dipenuhi oleh fenomena narasi baik tapi miskin relasi. Padahal sosok-sosok yang menghiasi ruang publik itu nyaris tak pernah terdengar kehadiran relasinya di level tapak atau basis masyarakat secara ikhlas. Singkatnya, orang-orang semacam itu tak pernah menggeluti dunia aktivisme maupun filantropi tapi mampu menarasikan dirinya sebagai sosok paling peduli pada kehidupan masyarakat kecil.
Sebagai publik, kita juga sudah menjadi sangat permisif melihat fenomena narasi baik tanpa relasi. Berdalih bahwa setiap orang berhak untuk mengklaim diri sebagai orang baik maka secara sadar kita telah menyuburkan perilaku semacam itu untuk tumbuh dalam kehidupan masa kini.
Sebuah tantangan
Lantas pertanyaannya apakah relasi baik tanpa narasi itu hanya akan menjadi kisah kearifan di ruang kelas sekolah saja? Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi kaum intelektual maupun profesional di negeri ini.
Sebagai praktisi komunikasi, membangun narasi dan relasi yang baik itu harusnya menjadi bagian terintegrasi yang harus dijalankan secara bersama-sama.
Strategi komunikasi yang baik itu selayaknya dirancang untuk menyelaraskan relasi dalam bentuk aktivitas atau kegiatan dengan narasi yang sepadan. Rasa-rasanya rumus komunikasi "membesarkan yang kecil dan mengecilkan yang besar" harus direfleksikan ulang.
Memang benar, dalam mengimplementasikan strategi komunikasi itu tidak selamanya semua informasi harus ditelanjangi ke ruang publik. Namun ada satu hal yang penting, yakni jangan pernah membohongi publik karena ingin menciptakan framming narasi atau informasi.
Sebagaimana diingatkan oleh founding father Amerika Serikat, Thomas Jefferson, sekali Anda membohongi publik maka sulit buat Anda dipercaya. Inilah yang kemudian dinamakan reputasi.
Artinya dalam membangun relasi dan narasi itu pada ujungnya adalah bagaimana memperkuat reputasi. Dalam kultur lokal negeri ini, sikap semacam itu bisa bercermin pada filosofi hidup orang Bugis, "Duduki kedudukanmu, tempati tempatmu". Filosofi ini bermakna mengambil sesuatu dari tempatnya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Narasi di era digital
Di era digital, hubungan narasi dan relasi ini kadang kala tidak mudah untuk berselaras. Kerap kali ditemui, persona-persona yang terlihat ramah, peduli atau humanis saat berkomunikasi di ruang virtual ternyata tidak seindah ketika sudah berinteraksi dalam kehidupan nyata mereka.
Semua perilaku itu sesungguhnya tak lepas dari sifat dasar manusia yang selalu ingin terlihat baik. Naluri dasar itulah yang kemudian tersalurkan melalui beragam platform digital melalui akun sosial media.
Dari sanalah kemudian lahir candu beraktivitas di dunia digital. Candu itu pada akhirnya melumpuhkan kreativitas kebaikannya di dunia nyata. Kelumpuhan ini semakin bertambah akut ketika pola komunikasi yang dibangun itu hanya sebatas mengejar trending atau percakapan yang tinggi di dunia digital saja tapi menjadi acuh dalam kehidupan nyata.
Tantangan perubahan perilaku inilah yang harus direspons secara bijak. Membangun narasi baik itu tentunya tak hanya cukup dalam ruang digital saja. Jauh lebih mendasar bagaimana kebaikan narasi itu bisa diwujudkan juga dalam implementasi kehidupan nyata, yang kelak bisa dilihat, disentuh atau juga dirasakan manfaatnya.
Untuk memulainya tentu saja harus dengan memotivasi diri untuk tidak membohongi publik. Perlu dicatat bahwa reputasi baik itu pada akhirnya melahirkan monumen-monumen kebaikan dalam bentuk narasi positif yang diperkuat oleh relasi yang baik dalam kehidupan nyata. Monumen-monumen inilah yang harusnya didorong untuk memperkuat reputasi para tokoh publik maupun lembaga.
Sebaliknya, kerja-kerja nyata dalam kebaikan sudah selayaknya untuk dinarasikan secara sepatutnya. Tentunya, mengabarkan kerja-kerja baik itu diniatkan sebagai wujud investasi untuk melahirkan generasi tanpa hipokrasi yang hanya gemar bernarasi baik tapi miskin relasi.
 Buruknya komunikasi publik, bersumber: diremehkannya logika publik oleh pemi...
Oleh Firman Kurniawan S
Buruknya komunikasi publik, bersumber: diremehkannya logika publik oleh pemi...
Oleh Firman Kurniawan S
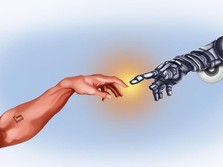 Dalam hal korelasi palsu, terdapat banyak korelasi dapat diungkap big data....
Oleh Firman Kurniawan S
Dalam hal korelasi palsu, terdapat banyak korelasi dapat diungkap big data....
Oleh Firman Kurniawan S
 Penulis melihat salah kaprah fungsi komunikasi di kementerian atau banyak or...
Oleh Algooth Putranto
Penulis melihat salah kaprah fungsi komunikasi di kementerian atau banyak or...
Oleh Algooth Putranto
 Konsep negara kesejahteraan yang telah digagas oleh para pendiri bangsa tela...
Oleh Rinaldi Malimin
Konsep negara kesejahteraan yang telah digagas oleh para pendiri bangsa tela...
Oleh Rinaldi Malimin