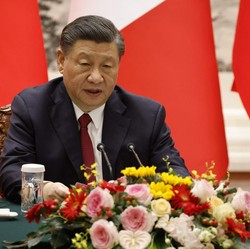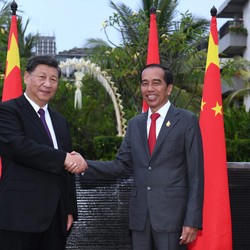
China Bisa Masuk Era "Tergelap" Lagi, RI Wajib Siaga Satu!

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Ekonomi China digadang-gadang bakal tumbuh kuat pada tahun ini, tetapi data berkata lain. Impor megalami penurunan tiga bulan beruntun, sementara kontraksi sektor manufaktur semakin dalam.
China mengalami masa "tergelap" dalam hal pertumbuhan ekonomi pada 2022 lalu. Produk domestik bruto (PDB) hanya tumbuh 3% sepanjang 2022, jika tidak memperhitungkan 2020 yang merosot akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi yang terendah dalam nyaris 50 tahun terakhir.
Banyak yang melihat China tidak bisa lagi mencapai pertumbuhan ekonomi dobel digit, bahkan rata-rata jangka panjang diperkirakan hanya 4%.
Michael Pettis, profesor finansial Guanghua School of Management di Peking University yang berlokasi di Beijing bahkan memprediksi pertumbuhan China tidak akan lebih tinggi dari 2% - 3% dalam beberapa tahun ke depan jika melakukan penyeimbangan ekonomi.
Dalam tulisannya yang dimuat oleh Carnegie Endowment, Pettis menyebut China negara dengan investasi sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia. Penyeimbangan ekonomi perlu dilakukan dengan mendorong lebih banyak konsumsi. Namun, ketika itu dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi China tidak akan lebih tinggi dari 3% selama bertahun-tahun, kecuali terjadi peningkatan konsumsi yang substansial.
Direktur Pelaksana Dana Moneter International (IMF) Kristalina Georgievapada akhir Maret lalu juga mendesak agar China segera melakukan penyeimbangan ekonomi, dari pertumbuhan yang ditopang oleh investasi ke konsumsi domestik.
Dalam pidatonya di China Development Forum Minggu (26/3/2023) di Beijing, Georgieva menyebut pertumbuhan yang ditopang konsumsi akan lebih tahan lama, tidak terlalu bergantung dengan utang, dan membantu mengatasi perubahan iklim.
Bukti masalah yang ditimbulkan dari pertumbuhan yang ditopang investasi kini sudah terlihat di China, utang pemerintah daerah (Pemda) dikabarkan menembus US$ 15,3 triliun atau hampir Rp 230.000 triliun (kurs Rp 15.000/US$). Bahkan, menurut estimasi Goldman Sachs nilainya mencapai US$ 23 triliun.
Kemudian sektor manufaktur China mengalami kontraksi yang cukup dalam. Artinya pabrik-pabrik mengalami penurunan aktivitas, misalnya produksi menurun. Dampaknya ke tenaga kerja, bukannya merekrut malah bisa jadi terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Hal ini terlihat dari purchasing managers' index (PMI) China Mei yang turun ke 48,8, terendah sepanjang tahun ini. PMI menggunakan angka 50 sebagai ambang batas, di bawahnya berarti kontraksi, sementara di atasnya ekspansi.
Sektor manufaktur yang berkontraksi juga terlihat dari impor China dilaporkan anjlok 4,5% pada Mei. Bahkan, anjloknya impor sudah terjadi dalam tiga bulan beruntun impor. Ekspor Indonesia ke China pun terancam. Terbukti pada April lalu, nilai ekspor Indonesia ke China jeblok 18,5% year-on-year (yoy).
Artinya, aktivitas perdagangan di China tetap memburuk, meskipun pembatasan Covid-19 telah dicabut.
Kontraksi sektor manufaktur China mulai menular ke RI. Maklum saja, China merupakan pasar ekspor terbesar, ketika mengalami kontraksi permintaan dari Negeri Tiongkok tentunya menurun. PMI manufaktur Indonesia juga nyaris mengalami hal yang sama.
S&P Global pagi ini melaporkan PMI manufaktur Indonesia sebesar 50,3 turun dari April sebesar 52,7. Pesanan baru dilaporkan mengalami kontraksi, yang membuat pertumbuhan produksi jadi melambat.
Jika terus berlanjut, tentunya pertumbuhan ekonomi RI terancam melambat. Sebab, sektor manufaktur merupakan kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kontribusinya mencapai 18,57%.
Selain itu, PHK massal juga kembali membayangi. Saat ini, 9 pabrik dilaporkan tengah dalam proses pemangkasan tenaga kerja, dimulai dengan merumahkan karyawan, menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi.
²©²ÊÍøվ INDONESIA RESEARCH
(pap/pap)